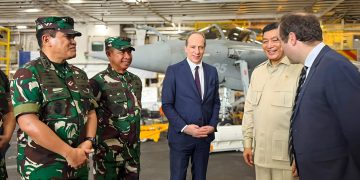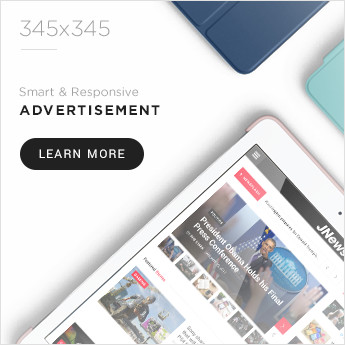Oleh: Buya Ki Jal Atri Tanjung (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Barat & Advokat Peradin)
Gema “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” kembali bergaung kencang di ranah Minang. Bukan sekadar pepatah adat yang terpampang di balai-balai, tetapi telah menjelma menjadi filosofi hidup yang kini mengukir tinta emas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Ada getar optimisme di sana.
Sumatera Barat sejatinya memiliki peluang emas untuk menghidupkan kembali khittahnya salah satunya melalui kehadiran Mahkamah Nagari.
Bayangannya sungguh elok: Mahkamah Nagari hadir sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat terendah. Lembaga ini berpotensi menyelesaikan sengketa waris, sengketa tanah ulayat, hingga pelanggaran adat secara “cepat, murah, dan berkeadilan.” Ini bukan sekadar mimpi di siang bolong—regulasinya sudah tersedia. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 membuka ruang, bahkan KUHP baru yang akan berlaku pada 2026 juga disebut mengakomodir eksistensi lembaga peradilan adat ini. Mahkamah Nagari diyakini mampu meredam “banjir perkara” yang selama ini menumpuk di Pengadilan Negeri.
Namun, di balik optimisme itu, muncul satu pertanyaan besar: di manakah “political will” Pemerintah Daerah?
Segudang regulasi ternyata tak cukup. Ia bak kapal megah yang tak kunjung berlayar karena nakhodanya ragu. Dukungan dari pusat dan desakan masyarakat seolah terbentur tembok birokrasi yang dingin. Implementasi Mahkamah Nagari tersendat, terjebak dalam wacana dan rapat-rapat yang tak kunjung menghasilkan keputusan konkret.
Paradoks pun muncul. Di satu sisi, UU Provinsi Sumbar disahkan dengan gegap gempita, mengukuhkan jati diri ABS-SBK. Namun di sisi lain, perwujudannya dalam bentuk lembaga peradilan adat yang nyata justru jalan di tempat. Seolah ada ketakutan untuk benar-benar menyerahkan sebagian kewenangan, atau mungkin ketidaktuntasan dalam merumuskan mekanisme operasionalnya.
Lebih jauh, dalam euforia pengesahan UU ini, suara dari Kepulauan Mentawai sempat teredam. Padahal, keberagaman budaya di Sumatera Barat tidak hanya Minangkabau. Karena itu, Mahkamah Nagari harus inklusif, tidak boleh mengabaikan komunitas adat lain yang juga hidup di bumi Andalas ini.
Masyarakat telah menunggu. Mereka lelah dengan proses hukum yang panjang, rumit, dan mahal. Mereka rindu akan keadilan yang dekat yang memahami konteks sosial dan kultural mereka. Mahkamah Nagari adalah jawaban atas kerinduan itu.
Kini saatnya Pemerintah Daerah tidak lagi setengah hati. Political will harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata: penyusunan aturan teknis, alokasi anggaran, serta sosialisasi yang masif ke seluruh nagari. Jangan biarkan Mahkamah Nagari hanya menjadi “ratu adil dalam dongeng,” sementara rakyat masih mencari-cari keadilan di pintunya sendiri.
Jangan sampai kita memiliki hukum nasional dan hukum adat, tetapi rakyat justru terjepit di antara keduanya.